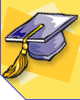Kapan Kita Memilki E-University ?
Publikasi majalah The Times di Inggris tentang nama-nama perguruan tinggi kelas dunia baru-baru ini ada sebagian yang menyedihkan dan ada sebagian lain yang membanggakan kita. Menyedihkan karena tidak ada satu pun pertguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam jajaran “elite“. Membanggakan karena salah satu perguruan tinggi Indonesia, yaitu UGM Johgjakarta, menjadi salah satu perguruan tinggi berkelas dunia (world university) untuk bidang ilmu tertentu.
Sepuluh perguruan tinggi terbaik kelas dunia tahun2006, Top 10 World Universites, adalah Harvard University (US), Massachusetts Institute of Technology (US), University of Cabridge (UK), University of Oxford (UK), Standford University (US), University of California Berkeley(US), Yale University(US), California Institute of Technology (US), Princeton University(US), dan Ecoley Polytechnique(UK).
Yang menyedihkan tidak ada satu pun perguruan tinggi di Indonesia yang masuk di dalamnya. Jangankan Indonesia, perguruan tinggi di Jepang, Singapura, dan Australia pun gagal. Yang membanggakan, UGM menjadi satu di antara 100 perguruan tinggi terbaik dunia untuk bidang ilmu-ilmu sosial (social sciences), ilmu-ilmu budaya dan humaniora (art adn humanities), dan ilmu-ilmu biomedis (biomedicines).
E-University
Sejumlah nama yang dipublikasikan The Times memang perguruan tinggi terbaik berkelas dunia untuk ukuran konvensional. Harvard University (US) misalnya,. Siapapun tahu lembaga itu memilki infra dan supra-struktur universitas yang memadai. Sebagian dosennya, selain memiliki gelar akademis yang memadai, doktor dalam disiplin ilmu yang mumpuni, memiliki pengalaman profesionalisme yang tak diragukan.
Banyak mantan penjabat pemerintah, dengan segala ilmu seperti pemerintahan, keuangan, politik, administrasi, bersedia menjadi dosen. Mantan direktur Bank Indonesia juga mejadi dosen di universitas ini.
Di samping menjadi perguruan tinggi terbaik dunia dalam ukuran konvensional, ternyata Harvard University pun menjadi perguruan tinggi “modern“ kelas atas; perguruan yang banyak menggunakan jasa teknologi informasi internet dalam mengakses ilmu dan informasi akademis lainnya.
Sebuah hasil studi yang barus saja dilakukan “Centro de Informacion Documentatcion Cientifica (CINDOC) dan Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) berhasil membuat daftar tiga ribu perguruan tinggi di dunia menurut familiartas civitas akademikanya dalam menggunakan internet untuk melakukan komunikasi akademik, seperti mengakses ilmu dan informasi, mempublikasi karya-karya ilmiah, serta melakukan kontak akademis dengan relasi.
Meskipun lembaga internasional tersebut tidak menggunakan istilah electronic-university atau e-university, penggunaan internet yang tinggi, baik frekuensi maupun efektivitasnya, sebenarnya sudah mengarah pada terbentuknya e-university.
Di antara tiga ribu perguruan tinggi terbaik dunai dalam penggunaan internet bagi civitas akademiknya, ternyata Havard University berhasil menempati ranking ke-2. Apakah artinya itu semua? Artinya, di samping terbaik dalam ukuran konvensional, ternyata Havard University pun juga terbaik (kedua) dalam ukuran modern.
Kalau kita sepakat bahwa perguruan tinggi yang akrab denga internet dalam melakukan komunikasi akademis bagi civitas akademikanya sebagai e-university, universitas jenis ini “diborong“ oleh perguruan tinggi di Amerika Serikat (AS).
Apabila kita cermati 50 perguruan tinggi terbaik, mulai ranking ke-1 hingga ke-50, Top 50 Webometrics Ranking of World Universities, 45 diantaranya adalah perguruan tinggi yang berkiprah di AS. Dimulai dari ranking ke-1 University of California Berkeley (US), ke-2 Harvard University (US), ke-3 Massachusetts Institute of Technology (US), sampai dengan ranking ke-50 University of Georgia (US) memang didominasi perguruan tinggi di AS.
Tanpa bermaksud mengkultuskan AS, kita harus mengakui kehebatan AS dalam berteknologi informasi. Di situlah kelebihan perguruan tinggi di AS jika dibandingkan denga perguruan tinggi di negara mana pun; termasuk di negara yang penguasaan teknologinya tergolong hebat seperti Inggris, Jerman, dan Jepanga. Sejujurnya, sekarang ini siapa pun tidak akan mampu belajar di AS kalu yang bersangkutan menderita gagap teknologi.
Bagaimana Indonesia? Apakah sudah ada perguruan tinggi kita yang civitas akademikanya akrab dengan internet dalam berkomuniasi akademis? Apakah sekarang kita sudah memiliki e-university sebagaimana perguruan tinggi di AS?
Untuk menjawab secara objektif pertanyaan tersebut, kita dapat membaca nama-nama perguruan tinggi terbaik versi CINDOC dan CSIC. Dari daftar 250 perguruan tinggi terbaik, Top 250 Webometrics Ranking of World Universities, ternyata tidak ada satupun nama perguruan tinggi di Indonesia yang muncul. Di luar perguruan tinggi di AS, memang banyak perguruan tingg yang muncul. Misalnya ranking ke-21 University of Oxford (UK), ke-32 University of Toronto (Canada), ke-159 National Taiwan University, dan ke-175 Kyoto University.
Apakah e-university terseut hanya dimiliki oleh negara-negara maju seperti AS, Inggris, dan Jerman? Oh, tidak! Di negara-negara berkembang pun ternyata mulai ada perguruan tinggi yang civitas akademianya akrab dengan internet. Di Mexico ada University Nacional Autonoma de Mexico, di Israel ada Hebrew University of Jerusalem, di Spanyol ada University Complutense Madrid, dsb. Civitas akademika perguruan tinggi di negara-negara berkembang ini pun sudah akrab dengan internet.
Jadi, e-university itu bukanlah mutlak milik negara maju. Di negara-negara berkembang pun ternyata banyak ditemui perguruan tinggi yang (berpotensi) menjadi e-university. Tetapi, perguruan seperti itu hanya berada pada negara yang pemerintahnya memang memiliki perhatian serius untuk mengembangkan sekaligus mengaplikasi teknologi informasi untuk kepentingan pendidikan. Sekali lagi, bagaimana di Indonesia ...?!!!.
*) Prof. Dr. Ki Supriyoko MPd, adalah Ketua Majelis Luhur Taman Siswa dan Wakil Presiden Pan-Pacific Association of Private Organization (PAPE) di Tokyo Jepang.
(Sumber Harian Indo-Pos- Jumat, 3 November 2006)
Bacaan Selanjutnya!
Sepuluh perguruan tinggi terbaik kelas dunia tahun2006, Top 10 World Universites, adalah Harvard University (US), Massachusetts Institute of Technology (US), University of Cabridge (UK), University of Oxford (UK), Standford University (US), University of California Berkeley(US), Yale University(US), California Institute of Technology (US), Princeton University(US), dan Ecoley Polytechnique(UK).
Yang menyedihkan tidak ada satu pun perguruan tinggi di Indonesia yang masuk di dalamnya. Jangankan Indonesia, perguruan tinggi di Jepang, Singapura, dan Australia pun gagal. Yang membanggakan, UGM menjadi satu di antara 100 perguruan tinggi terbaik dunia untuk bidang ilmu-ilmu sosial (social sciences), ilmu-ilmu budaya dan humaniora (art adn humanities), dan ilmu-ilmu biomedis (biomedicines).
E-University
Sejumlah nama yang dipublikasikan The Times memang perguruan tinggi terbaik berkelas dunia untuk ukuran konvensional. Harvard University (US) misalnya,. Siapapun tahu lembaga itu memilki infra dan supra-struktur universitas yang memadai. Sebagian dosennya, selain memiliki gelar akademis yang memadai, doktor dalam disiplin ilmu yang mumpuni, memiliki pengalaman profesionalisme yang tak diragukan.
Banyak mantan penjabat pemerintah, dengan segala ilmu seperti pemerintahan, keuangan, politik, administrasi, bersedia menjadi dosen. Mantan direktur Bank Indonesia juga mejadi dosen di universitas ini.
Di samping menjadi perguruan tinggi terbaik dunia dalam ukuran konvensional, ternyata Harvard University pun menjadi perguruan tinggi “modern“ kelas atas; perguruan yang banyak menggunakan jasa teknologi informasi internet dalam mengakses ilmu dan informasi akademis lainnya.
Sebuah hasil studi yang barus saja dilakukan “Centro de Informacion Documentatcion Cientifica (CINDOC) dan Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) berhasil membuat daftar tiga ribu perguruan tinggi di dunia menurut familiartas civitas akademikanya dalam menggunakan internet untuk melakukan komunikasi akademik, seperti mengakses ilmu dan informasi, mempublikasi karya-karya ilmiah, serta melakukan kontak akademis dengan relasi.
Meskipun lembaga internasional tersebut tidak menggunakan istilah electronic-university atau e-university, penggunaan internet yang tinggi, baik frekuensi maupun efektivitasnya, sebenarnya sudah mengarah pada terbentuknya e-university.
Di antara tiga ribu perguruan tinggi terbaik dunai dalam penggunaan internet bagi civitas akademiknya, ternyata Havard University berhasil menempati ranking ke-2. Apakah artinya itu semua? Artinya, di samping terbaik dalam ukuran konvensional, ternyata Havard University pun juga terbaik (kedua) dalam ukuran modern.
Kalau kita sepakat bahwa perguruan tinggi yang akrab denga internet dalam melakukan komunikasi akademis bagi civitas akademikanya sebagai e-university, universitas jenis ini “diborong“ oleh perguruan tinggi di Amerika Serikat (AS).
Apabila kita cermati 50 perguruan tinggi terbaik, mulai ranking ke-1 hingga ke-50, Top 50 Webometrics Ranking of World Universities, 45 diantaranya adalah perguruan tinggi yang berkiprah di AS. Dimulai dari ranking ke-1 University of California Berkeley (US), ke-2 Harvard University (US), ke-3 Massachusetts Institute of Technology (US), sampai dengan ranking ke-50 University of Georgia (US) memang didominasi perguruan tinggi di AS.
Tanpa bermaksud mengkultuskan AS, kita harus mengakui kehebatan AS dalam berteknologi informasi. Di situlah kelebihan perguruan tinggi di AS jika dibandingkan denga perguruan tinggi di negara mana pun; termasuk di negara yang penguasaan teknologinya tergolong hebat seperti Inggris, Jerman, dan Jepanga. Sejujurnya, sekarang ini siapa pun tidak akan mampu belajar di AS kalu yang bersangkutan menderita gagap teknologi.
Bagaimana Indonesia? Apakah sudah ada perguruan tinggi kita yang civitas akademikanya akrab dengan internet dalam berkomuniasi akademis? Apakah sekarang kita sudah memiliki e-university sebagaimana perguruan tinggi di AS?
Untuk menjawab secara objektif pertanyaan tersebut, kita dapat membaca nama-nama perguruan tinggi terbaik versi CINDOC dan CSIC. Dari daftar 250 perguruan tinggi terbaik, Top 250 Webometrics Ranking of World Universities, ternyata tidak ada satupun nama perguruan tinggi di Indonesia yang muncul. Di luar perguruan tinggi di AS, memang banyak perguruan tingg yang muncul. Misalnya ranking ke-21 University of Oxford (UK), ke-32 University of Toronto (Canada), ke-159 National Taiwan University, dan ke-175 Kyoto University.
Apakah e-university terseut hanya dimiliki oleh negara-negara maju seperti AS, Inggris, dan Jerman? Oh, tidak! Di negara-negara berkembang pun ternyata mulai ada perguruan tinggi yang civitas akademianya akrab dengan internet. Di Mexico ada University Nacional Autonoma de Mexico, di Israel ada Hebrew University of Jerusalem, di Spanyol ada University Complutense Madrid, dsb. Civitas akademika perguruan tinggi di negara-negara berkembang ini pun sudah akrab dengan internet.
Jadi, e-university itu bukanlah mutlak milik negara maju. Di negara-negara berkembang pun ternyata banyak ditemui perguruan tinggi yang (berpotensi) menjadi e-university. Tetapi, perguruan seperti itu hanya berada pada negara yang pemerintahnya memang memiliki perhatian serius untuk mengembangkan sekaligus mengaplikasi teknologi informasi untuk kepentingan pendidikan. Sekali lagi, bagaimana di Indonesia ...?!!!.
*) Prof. Dr. Ki Supriyoko MPd, adalah Ketua Majelis Luhur Taman Siswa dan Wakil Presiden Pan-Pacific Association of Private Organization (PAPE) di Tokyo Jepang.
(Sumber Harian Indo-Pos- Jumat, 3 November 2006)